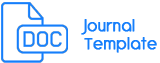Posisi Obskur Psikologi Kualitatif
(1) Faculty of Psychology, Sanata Dharma University
(*) Corresponding Author
Abstract
Pada mulanya adalah perihal obskur. Psikologi Kualitatif diposisikan seperti anak tiri dalam Psikologi. Secara teoretis dan metodologis, pendekatan kualitatif tidak diragukan eksistensinya. Namun secara praktis penelitian, pendekatan kualitatif tampak dan terdengar seperti wilayah yang jauh dan teramat asing, setidaknya dalam peta psikologi mainstream. Sejak awal kelahiran Psikologi, pendekatan kualitatif telah eksis sebagai sebuah tradisi berpikir tersendiri, yang misalnya dicomot dari tradisi fenomenologi. Bahkan, dalam karya-karya Wilhelm Wundt (1832-1920) dan William James (1842-1910) – dua tokoh awal Psikologi – kedudukan unsur subjektif dan objektif telah menjadi bagian dalam pembahasan risalah intelektual. Kedua tokoh tidak luput membicarakan makna, budaya, dan identitas yang kerap kali menjadi diskusi serius dalam tradisi kualitatif. Selain itu, apabila dicermati dengan sungguh, psikoanalisis yang dikembangkan Sigmund Freud (1856-1932) memanfaatkan wawancara dan serakan data remeh sebagai dasar dalam memahami psikologi subjek. Namun, mengapa pendekatan kualitatif seolah-olah begitu obskur?
Menurut Danziger (1990), keberadaan pendekataan kualitatif sebagai “the excluded” dalam Psikologi dimulai dari penelitian-penelitian yang dianggap menjadi ciri khas Psikologi. Dalam sejarah keilmuan Psikologi sejak 1800an hingga hari ini, terjadi pergeseran dalam cara kerja penelitian yang tadinya dipraktikkan dengan pencatatan lewat observasi kemudian direduksi menjadi respons diri yang bersifat naif. Dalam eksperimen, yang dicatat si peneliti adalah respons perilaku dan bukan mental (mind) manusia. Oleh karena itu, intensi Psikologi untuk menangkap dan mengeksplorasi “mind” berubah menjadi pencatatan respons perilaku. Artinya, penelitian Psikologi cenderung menjadi ilmu mengenai mind terhadap mindless individual (Rogers & Willig, 2017).
Apa yang ditunjukkan di atas adalah cara manusia untuk menjawab bagaimana dan apa yang bisa diketahui. Dalam tradisi keilmuan, hal demikian diperdebatkan melalui Epistemologi. Cabang Filsafat tersebut upaya untuk menjawab mengenai bagaimana suatu pengetahuan diperoleh. Dalam tradisi Psikologi yang dominan (mainstream psychology), epistemologi yang bekerja adalah positivis (Rogers & Willig, 2017; Willig 2008, 2013). Epistemologi positivis dalam keilmuan dapat ditelusur secara historis untuk kemudian akan ditemukan beberapa modelnya, yakni positivisme klasik, positivisme kritis, dan positivisme logis (Rogers & Willig, 2017). Secara umum, dalam ketiga model positivisme tersebut, subyektivitas, sejarah, dan masyarakat menjadi tidak relevan untuk menentukan kebenaran pengalaman. Seorang peneliti perlu melakukan isolasi terhadap manusia agar kebenaran dapat diperoleh. Apa yang digagas Karl Popper (1902-1994) sebagai rasionalisme kritis juga memiliki asumsi serupa, sehingga sekalipun ia memberi kritik terhadap positivisme, tetapi ia dianggap sebagai seorang positivis (Ormerod, 2009).
Secara dominan, Teo (2018) menunjukkan bahwa tradisi berpikir ala Popper direproduksi dengan keyakinan dari filsafat pengetahuan yang menunjukkan bagaimana suatu pernyataan keilmuan dapat dijustifikasi atau disebut dengan konteks justifikasi (context of justification). Karena penekanan pada justifikasi, maka konteks penemuan (context of discovery) atau pertanyaan mengapa suatu ilmu berminat pada suatu pertanyaan, bukan lagi menjadi hal yang menjadi perhatian serius. Sebagai implikasi, peneliti akan cenderung berminat pada kecanggihan metodologi alih-alih asal-usul sosiohistoris disiplin Psikologi, termasuk di dalamnya adalah subyektivitas peneliti. Ketiadaan dimensi sosiohistoris tersebut akan membatasi peneliti psikologi untuk tidak melibatkan minat personal dalam rangka mengarahkan cara pandang terhadap dunia (Willig, 2013). Problem yang muncul kemudian adalah ketidakmungkinan untuk netral secara murni, seseorang senantiasa melakukan penciptaan makna mengenai objek tertentu yang terbangun selama pengalaman hidupnya.
Tradisi berpikir positivis dengan berbasis pada konteks justifikasi tersebut kemudian dikritik oleh seorang pemikir bernama Thomas Kuhn (1922-1996) yang menyatakan bahwa dalam proses keilmuan terdapat elemen yang melampaui-yang-logis dan melampaui-yang-rasional yang kemudian nantinya akan berujung pada sejarah dan sosiologi ilmu pengetahuan dalam cabang Epistemologi. Secara khusus, kelemahan dari perspektif positivis adalah absennya sejarah, budaya, dan masyarakat dalam upaya menjelaksan serta memahami dunia. Menurut Teo (2018), proses dalam keilmuan tidak hanya konteks justifikasi, melainkan juga konteks penemuan, konteks interpretasi (context of interpretation), dan konteks aplikasi (context of application). Bahkan, konteks justifikasi sendiri nyatanya tidak luput dari subjektivitas peneliti. Letak Psikologi sebagai ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial mestinya juga memposisikan Psikologi tidak hanya berfokus pada kecanggihan metodologi untuk memotret kehidupan individual, melainkan juga menempatkan pengalaman subjektif individual dalam tegangan antara subjek dengan sistem (Keucheyan, 2011).
Bergeser dari tradisi positivis, tokoh Psikologi asal Jerman, yakni Klauz Holzkamp (1927-1995), menyebut tradisi dalam Psikologi dengan istilah yang sangat tepat, yakni realisme naif (naive realism) (Holzkamp, 1972). Realisme naif berupaya menggambarkan penelitian empiris sebagai cerminan dunia luar dengan meminimalisasi bias, menanggalkan gagasan sebelumnya (purifikasi), dan melakukan penetralan metodologi. Dengan melakukan purifikasi tersebut, maka tradisi berpikir Psikologi mengasumsikan tidak terdapat dimensi societal atau historis. Persoalannya kemudian adalah bahwa sebuah persepsi beroperasi secara selektif dan orang bisa melihat satu hal dengan cara yang berbeda, tergantung dari tujuan pengamatan yang dilakukan (Rogers & Willig, 2017).
Selain tradisi positivis dan realisme naif, problem lain yang ditunjukkan dalam filsafat ilmu adalah hypothethico-deductivism (Willig 2008, 2013). Gagasan tersebut dimulai dari kritik Popper tehadap induktivisme yang tidak bisa memberikan pernyataan kategoris seperti “a mengikuti b”. Dalam induktivisme, tidak dapat dipastikan bahwa kejadian selanjutnya akan mengikuti pola “a mengikuti b”. Karena tidak tertebak, maka akan muncul kesulitan untuk melakukan verifikasi. Lantas Popper mengusulkan bahwa sebuah ilmu sebaiknya menganut sistem deduksi dan falsifikasi, misalnya dengan membuat hipotesis di awal. Dengan adanya falsifikasi, maka akan bisa ditentukan mana yang benar dan tidak benar.
Kontras dengan tradisi positivis dan realisme naif, Henwood (2014) menyatakan bahwa seorang peneliti kualitatif mensyaratkan keterlibatan aktif peneliti pada dunia yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, peneliti kualitatif mestinya melakukan pengamatan yang jeli, mendengarkan, merekam, dan mengkontekstualisasikan pengalaman nyata, pikiran, tindakan, dan refleksi manusia untuk kemudian melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari hasil proses tersebut. Sekalipun demikian, proses interpretasi ini bukan “barang” baru dalam penelitian Psikologi. Sebagaimana ditunjukkan dalam oleh Danziger (1990) proses interpretasi (atau yang lebih subtil, yakni introspeksi) tergeser dan terdominasi oleh penelitian eksperimen dan survei yang tadinya peneliti menjadi subjek pengamat menjadi pencari respons. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa selama kurun waktu satu abad lebih sejarah ilmu Psikologi, pendekatan kualitatif cenderung tersembunyi (hidden) dalam berbagai hasil penelitian.
Sifat tersembunyi atau obskur tersebut muncul sebagai gejala methodolatry dalam Psikologi. Methodolatry merupakan kecenderungan untuk menghindari teori dan mengidolakan metode yang dianggap bisa menggambarkan keahlian tertentu dari peneliti (Rogers & Willig, 2017). Kecenderungan methodolatry ini kemudian membuat keilmuan dalam ranah para ahli saja. Dengan demikian, rezim ilmu pengetahuan sebagai digagas Foucault (1969/2002), dengan terang-terangan menampilkan diri pada perkembangan penelitian Psikologi. Apabila dicermati, struktur jurnal Psikologi cenderung memberi porsi bagian diskusi yang cukup minim, artinya proses interpretasi dan kemungkinan untuk membuka ruang alternatif terhadap pemahaman suatu fenomena bukan menjadi perkara yang penting untuk dielaborasi.
Agaknya, kecenderungan methodolatry tersebut mengalami perlawanan yang cukup sengit dari para pemikir yang tidak puas dengan penjelasan kuantitatif. Setidaknya, ada dua palingan yang secara pelan tapi pasti berupaya untuk melakukan resistensi dengan pendekatan yang terlampau realisme naif. Palingan tersebut adalah palingan bahasa (language turn) dan palingan interpretasi (interpretation turn) (Rogers & Willig, 2017). Kedua paling tersebut bermula dari metode interpretasi dan kesadaran sebagai subjek studi yang dikesampingkan oleh Psikologi mainstream. Sebagai contoh adalah kelahiran Psikologi Feminis yang berupaya mempertanyakan mengapa dalam penelitian Psikologi (juga penelitian sosial) cenderung menemukan atau mengkonfirmasi kemampuan intelektual dan karakter moral perempuan yang digambarkan inferior. Oleh karena itu, persoalannya bukan sekadar inferioritas perempuan, melainkan lebih pada inferiorisasi perempuan (Gilligan, 1982; bdk. Žižek, 2009).
Pada palingan pertama, yakni palingan bahasa, ditunjukkan bahwa bagaimana cara seseorang berbicara dan merepresentasikan realitas berkontribusi dalam mengekspresikan mentalitas orang tersebut. Dalam palingan bahasa, seorang peneliti akan berfokus pada konstruksi makna. Palingan ini muncul secara gradual sejak 1930an dalam gerakan ilmu kemanusiaan dan seni surealisme (Roudinesco, 1993/1997) – yang kemudian berpuncak di Psikologi pada sekitar 1980an dan 1990an (Rogers & Willig, 2017). Sumbangan besar palingan bahasa adalah membawa kesadaran bahwa bahasa bukanlah produk kultural yang netral. Dalam kajian ilmu yang lain, palingan bahasa ini disebut dengan palingan budaya (cultural turn). Sifat kultural dari bahasa menunjukkan bahwa wicara atau produk yang diekspresikan oleh seseorang merupakan interseksi dari subjek dan sistem sosial yang lebih luas. Palingan bahasa ini membuka kemungkinan untuk suatu analisis yang mempertimbangkan konteks atau saat dan tempat ketika seseorang mengekpresikan gagasannya mengenai dunia.
Sebab sebuah makna dikonstruksi sebagaimana diyakini palingan bahasa, maka kemudian dalam palingan interpretasi penekanan pada penciptaan makna (meaning-making) menjadi pusat analisis (Rogers & Willig, 2017). Dalam sejarah pendekatan kualitatif, ada dua cara memahami bahasa. Pertama adalah bahwa peneliti meyakini bahwa bahasa merupakan ekspresi jujur dan murni dari kesadaran. Cara pertama ini ditampilkan dalam model fenomenologi deskriptif. Bahwa apa yang disampaikan subjek penelitian merupakan suatu kebenaran yang tidak lagi perlu melalui interpretasi, peneliti cukup melakukan pengelompokkan tema untuk kemudian mendeskripsikan pengalaman. Cara kedua adalah sebagaimana dimanifestasikan oleh fenomenologi interpretatif dan tradisi konstruksionisme. Bahwa suatu ungkapan atau bahasa muncul dari konteks yang menghadirkan subjek pewicara. Dalam cara kedua ini, peneliti akan mendemonstrasikan analisis yang berbasis data (grounded in data) sekaligus konsisten scara teoretis (theoretically driven).
Menurut Rogers dan Willig (2017), apa yang membedakan model deskriptif dan interpretatif adalah bahwa penelitian interpretatif berupaya memproduksi pemahaman mengenai bagaimana seseorang mengalami dunia dan dirinya dengan cara yang khusus. Oleh karena keunikan pengalaman ini, maka diasumsikan ada fenomena sosial yang perlu diidentifikasi dan dijelaskan dengan detail. Fenomena sosial inilah yang dianggap tersembunyi dan perlu diuraikan untuk memahami (bukan sekadar menjelaskan) cara pandang terhadap dunia, perilaku, dan pengalaman seseorang. Bahkan interpretasi ini bukanlah perkara yang sudah final, sebuah interpretasi perlu membuka ruang kemungkinan bahwa ada alternatif interpretasi lain. Kekeliruan diasumsikan akan senantiasa membayangi analisis yang dianggap benar dan bahwa kebenaran itu sendiri tidak bisa dipastikan tunggal. Lantas, dalam model interpretatif, tantangannya adalah melampaui apa yang tampak, dengan harapan bisa menyingkap dimensi tersembunyi sekaligus tidak memaksakan makna yang mendasari suatu fenomena psikologis.
Persoalan palingan bahasa, palingan budaya, maupun palingan interpretasi ini kemudian dalam perkembangan kontemporer mulai melirik pada palingan afek (affective turn) yang diinisiasi oleh Brian Massumi (1987, 2015) dan Patricia Clough (2008). Palingan afek ini menampilkan bahwa afek merupakan pengalaman fisiologis yang bersifat pra-subjektif sebelum rasionalitas dan intensionalitas hadir. Dalam afek, bahasan seperti kenikmatan (pleasure and joy), luka dan duka (pain and mourning), serta hasrat (desire) menjadi fokus yang dieksplorasi. Meskipun demikian, afek juga bukan sesuatu yang bersifat alamiah. Kesenangan atau hasrat seseorang senantiasa tidak berada dalam ruang kosong. Artinya, aspek fluiditas dan keterikatan pada konteks menjadi bagian yang tidak bisa tidak untuk dipahami dalam sebuah penelitian (Gough, 2017).
Pemahaman pada konteks yang dipadu dengan posisionalitas peneliti ini kemudian juga membuka ruang baru untuk melakukan penelitian yang sifatnya tidak eksploitatif dan justru membebaskan manusia, misalnya gerakan decolonializing psychology (dekolonisasi Psikologi) (Bhatia, 2017). Dekolonisasi merupakan upaya untuk melakukan pergeseran dari etic menjadi emic (insider’s perspective) sebagaimana juga terjadi dalam pendekatan budaya dalam Psikologi (Matsumoto & Juang, 2013; Ratner, 2006). Tradisi berpikir dekolonial ini agaknya juga perlahan menjadi tren yang tengah berlangsung dalam penelitian psikologi yang berfokus pada “kebutuhan akan keragaman, keadilan, dan inklusi dalam konten ilmiah serta mengambil langkah untuk memperbaiki praktik yang rasis dan berprasangka selama berdekade lamanya” (Santoro, 2023 hlm. 50). Warisan kolonialisme, orientalisme, maupun Eurosentris yang tampil dalam subjek penelitian Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic (WEIRD) nyatanya tidak memuaskan untuk menjelaskan konteks negara global belahan bumi Selatan (Global South) maupun komunitas yang tersingkir (Santoro, 2023).
Model psikologi yang inklusif dan berkeadilan demikian berupaya untuk menempatkan diri bahwa penelitian dan interpretasi bukan hal yang netral dan secara etis justru berimplikasi semakin memangkirkan mereka yang tersingkir. Bahkan, dalam perkembangan di Psikologi, penelitian kuatitatif nyatanya juga membuka arena baru bernama QuantCrit (Quantitative Critical Theory) yang meyakini bahwa angka tidak netral, kategori tidak natural, data tidak bisa berbicara sendiri dan membutuhkan penyuaraan, serta kebutuhan untuk mempertimbangkan keadilan (sosial). Lantas, alih-alih sekadar berfokus pada metodologi yang digunakan, sebuah penelitian pertama-tama perlu untuk berfokus pada episteme atau logika yang mungkin saja pincang sedari peneliti membangun problematisasi. Dengan demikian, refleksivitas menjadi hal yang senantiasa diperlukan dalam proses penelitian dengan harapan bahwa ada kejelian dan ketelatenan proses penelitian, entah batasan apa yang dimiliki peneliti, kemungkinan adil-tidaknya cara berpikir, atau bahkan implikasi dari temuan penelitian.
Berbarengan dengan tren global perkembangan disiplin Psikologi, Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma Vol. 4, No. 1 kali ini didominasi oleh pendekatan yang bersifat eksploratif dengan memanfaatkan data kualitatif. Pemanfaatan data kualitatif tersebut selaras gagasan Arellano (2022) yang menyatakan bahwa berbagai jurnal hasil penelitian yang tersaji perlu membuat perubahan transformasional dengan mendengarkan cerita pengalaman dari para subjek. Orang perlu terhubung pada ranah emosi manusia yang (kebetulan) hanya dapat diperoleh lewat data kualitatif. Secara detail, terdapat enam tulisan bernuansa kualitatif, dengan detail sebanyak lima penelitian berbasis pada pengambilan data terhadap para informan dan satu tulisan berbasis studi arsip.
Pada tulisan pertama, Supratiknya dkk. (2023) berupaya mengungkap aspek formatif dalam pola komunikasi guru-siswa dalam konteks pembelajaran di Sekolah Dasar (SD). Berbasis pada gagasan Empat Wacana (Four Discourses) yang diinisiasi oleh Jacques Lacan (1901-1981), seorang psikoanalis Perancis, tulisan tersebut mengidentifikasi tipe wacana yang digunakan dalam proses komunikasi di kelas. Lacan merupakan figur besar psikoanalisis yang kembali ke Freud (return to Freud) dengan pendekatan Hegelian dan semiologi. Rahim interdisiplin yang dikembangkan Lacan ini menandai bahwa cara pandang Psikologi yang dikawinkan dengan pendekatan keilmuan lain berpotensi untuk memberi kesegaran pemahaman terhadap pengalaman komunikasi di kelas, terlebih dalam kajian mengenai formasi subjek.
Tulisan kedua mengembangkan gagasan komunikasi di kelas pada level Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan memanfaatkan pengolahan data Analisis Tematik (Thematic Analysis) tipe realis. Ketiga penulis, yakni Justin, Widiyanto, dan Kristiyani, memanfaatkan analisis tematik dengan harapan bisa menangkap dan mengeksplorasi pengalaman komunikasi dengan tidak mengesampingkan perkembangan komunikasi secara daring. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengalaman komunikasi secara langsung (luring) menciptakan ekosistem yang membuat transmisi pengetahuan guru-siswa menjadi lebih efektif dan nyaman.
Selanjutnya, dalam tulisan ketiga, Putri dan Hidajat mengeksplorasi pengalaman dukacita yang dialami oleh individu dewasa awal yang mengalami kehilangan sanak-saudara selama pandemi Covid-19. Dalam eksplorasi tema secara kualitatif yang dilakukan, kedua peneliti secara khusus berfokus pada pertumbuhan pasca-trauma (post-traumatic growth). Melalui penelitian ini, Putri dan Hidajat menemukan bahwa dalam ruminasi kedukaan, makna dan perbedaan kepribadian menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses intervensi terhadap rasa duka yang dialami para informan.
Melalui Analisis Fenomenologi Interpretif (Interpretative Phenomenological Analysis), tulisan keempat akan mengeksplorasi mengenai pandangan petani terhadap lembaga pendidikan. Tulisan Handayani dilatarbelakangi oleh fakta obyektif bahwa tingkat pendidikan di daerah pedesaan cenderung lebih rendah daripada orang-orang yang tinggal di perkotaan. Bagi para petani yang tinggal di area pedesaan, Handayani mengungkapkan bahwa pada kenyataannya sekolah juga dianggap sebagai ruang penting untuk dinikmati oleh keluarga mereka. Bahkan, keluarga petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mempersepsikan sekolah sebagai ruang transformasional bagi para agen yang mengenyam pendidikan di dalamnya.
Kemudian, dalam tulisan kelima, Hartoko memanfaatkan kombinasi merodologi kuantitatif dan kualitatif dengan perspektif representasi sosial guna mencermati cara orang muda dalam memahami demokrasi. Perspektif representasi sosial, yang digagas Serge Moscovici (1925-2014) berusaha untuk menangkap strukturasi gagasan yang diyakini para subjek. Melalui pengambilan data survei kualitatif, Hartoko mengidentifikasi gagasan orang muda mengenai demokrasi yang tercermin dalam kebebasan berpendapat, keberagaman dan kesetaraan, serta keadilan. Ketiga gagasan tersebut menunjukkan nilai-nilai dasar pembentukan kewargaan dan kebutuhan orang muda untuk berpartisipasi sekaligus independen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tulisan keenam, atau terakhir, memanfaatkan studi arsip untuk melihat perkembangan wacana pendidikan dan layanan psikologi. Dalam tulisan tersebut, Justin dan Supratiknya berupaya menawarkan orientasi pendidikan psikologi profesional di Indonesia. Secara khusus, kedua penulis mengeksplorasi dan melakukan komparasi kurikulum program profesi dan program akademik. Studi arsip ini kemudian menampilkan beberapa usulan kompetensi mengenai program profesi yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan menyusun kurikulum program profesi.
Kembali pada bagian awal mengenai sejarah dan perkembangan Psikologi Kualitatif dan disiplin ilmu Psikologi, keenam tulisan yang terkumpul agaknya menjadi simptom yang menunjukkan bahwa ada semacam gerakan yang pelan tapi pasti menuju pada model Psikologi yang sifatnya eksploratif dan jauh dari pendekatan arus utama yang cenderung positivistik. Sekalipun kecenderungan tersebut dirayakan secara kecil-kecilan dan obskur, tidak bisa dipungkiri bahwa ada transgresi yang melekat dalam tubuh disiplin Psikologi. Transgresi tersebut dilakukan melalui membuka celah-celah baru dalam penelitian yang tidak melulu bersifat realisme naif dan empirisis serta memanfaatkan data kualitatif.
Meskipun demikian, gagasan keterikatan pada konteks (context-bound), fluiditas fenomena, dan aspek posisionalitas peneliti belum secara khusus memperoleh ruang analisis yang tebal dan mendalam (thick description) dalam keenam tulisan yang tersaji. Pada akhirnya, bukan sesuatu yang muluk-muluk apabila berbagai tulisan dalam terbitan Suksma kali ini diharapkan menciptakan riak dalam keilmuan Psikologi yang selama ini didominasi oleh problem abstraksi dan kuantifikasi. Struktur kekuasaan dalam pengetahuan dan praktik hidup sehari-hari sebagaimana direpresentasikan memalui keenam tulisan barangkali juga telah digemakan beberapa dekade lalu: “Di mana ada kekuasaan,” ungkap Foucault (1978), “di sanalah hadir resistensi.”
Full Text:
PDFReferences
Arellano, L. (2022). Questioning the science: How quantitative methodologies perpetuate inequity in higher education. Education Sciences, 12(2), 116. http://dx.doi.org/10.3390/educsci12020116
Bhatia, S. (2017). Decolonizing psychology: Globalization, social justice, and Indian youth identities. Oxford University Press.
Clough, P. T. (2008). The affective turn. Theory, Culture & Society, 25(1), 1-22. doi:10.1177/0263276407085156
Danziger, K. (1990). Constructing the subject: Historical origins of psychological research. Cambridge University Press.
Foucault, M. (1969/2002). The archaeology of knowledge (Penerj. A. M. Sheridan Smith). Routledge.
Foucault, M. (1978). The history of sexuality, vol. 1: An introduction (Penerj. Robert Hurley). Pantheon.
Gilligan, C. (1982). In a different voice. Harvard University Press.
Gough, B. (2017). Critical social psychology: Mapping the terrain. Dalam B. Gough (ed.), The Palgrave handbook of critical social psychology (1-14). Palgrave Macmillan.
Keucheyan, R. (2013). The left hemisphere: Mapping critical theory today. Verso.
Massumi, B. (1987). Notes on the translation and acknowledgements. Dalam G. Deleuze dan F. Guattari (ed.), A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia (xvi–xx). University of Minnesota Press.
Massumi, B. (2015). Politics of affect. John Wiley & Sons.
Matsumoto, D. & Juang, L. (2008). Culture and psychology (ed.ke-5). Wadsworth.
Ormerod, R. J. (2009). The history and ideas of critical rationalism: The philosophy of Karl Popper and its implications for OR. Journal of the Operational Research Society, 60(4), 441–460. doi:10.1057/palgrave.jors.2602573
Ratner, C. (2006). Cultural psychology: A perspective on psychological functioning and social reform. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Rogers, W.S. & Willig, C. (2017). Introduction. Dalam W.S. Rogers & C. Willig, The SAGE handbook of qualitative research in psychology (1-13). SAGE Publications.
Roudinesco, É. (1993/1997). Jacques Lacan (Penerj. Barbara Bray). Columbia University Press.
Santoro, H. (2023). Psychological research is changing. Monitor on Psychology, Jan/Feb, 49-52.
Teo, T. (2010). What is epistemological violence in the empirical social sciences? Social and Personality Psychology Compass, 4(5), 295–303.
Teo, T. (2018). Outline of theoretical psychology. Palgrave Macmillan.
Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology (ed.ke-2). Open University Press.
Žižek, S. (2008). Violence. Picador.
DOI: https://doi.org/10.24071/suksma.v4i1.6245
Refbacks
- There are currently no refbacks.