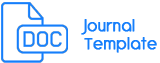Komitmen Organisasi yang Berpihak Subjek: Refleksi Kritis Praktik Organisasi
(1) Faculty of Psychology, Sanata Dharma University
(2) Universitas Sanata Dharma
(*) Corresponding Author
Abstract
Ketika seseorang membicarakan “organisasi” dalam konteks Psikologi kontemporer, imaji dominan yang muncul adalah suatu perusahaan atau organisasi yang mengakumulasikan kapital. Bahkan dalam Program Studi Psikologi di berbagai universitas di Indonesia, terdapat bidang Psikologi Industri dan Organisasi (PIO). Dalam sejarahnya, PIO dimulai dari Psikologi Industri yang berkembang pada awal abad ke-20. Penyandingan kata “industri” dengan “organisasi” baru muncul sekitar tahun 1970an (Riggio, 2012). Isu-isu yang dibahas pun berkembang, dari motivasi dan perencanaan tujuan, sikap kerja, dinamika kelompok, kekuatan organisasi, pengembangan organisasi, hingga kesejahteraan dan performansi kerja. Dengan kata lain, PIO berupaya untuk mengembangkan organisasi sekaligus manusianya.
Namun, apakah mungkin tujuan organisasi benar-benar dapat mewakili tujuan individu? Pertanyaan ini layak dikaji dalam praktik organisasi hari ini, di mana keduanya menjadi entitas yang sering kali berada dalam kondisi berhadapan: subjek individu dan organisasi. Dalam banyak kajian, relasi antara individu dan organisasi lebih sering terjadi pelemahan otonomi individu demi kepentingan organisasi yang semakin kuat (Kahn, 1990). Logika organisasi cenderung meletakkan posisi individu di bawah kepentingan yang dikendalikan oleh owner, atau sesuai dengan “kehendak” organisasinya (Deci et al., 2017).
Secara operasional, kepentingan owner, pemilik modal, atau pemberi kerja (employer) ini diterjemahkan ke dalam visi dan misi organisasi, untuk kemudian dipromosikan sebagai rules yang meregulasi individu di dalamya (Akter, 2021). Kepentingan yang mewujud dalam ide-ide besar tentang kemajuan, inovasi, dan efisiensi versi organisasi terkesan jarang mempertimbangkan aspirasi dan makna personal individu dalam posisinya sebagai anggota organisasi (baca: pekerja, buruh, karyawan, atau employee). Dari sudut pandang kritis, perspektif ini mengarah pada suatu bentuk kontrol hegemonik di mana individu dikondisikan untuk menerima dan melaksanakan aturan dan nilai-nilai organisasi tanpa perlu mempertanyakan. Sebagaimana dicatat oleh Lewandowski (2017), organisasi sering menggunakan mekanisme ideologis untuk membentuk nilai identitas individu sebagai karyawan, sebagai bahasa halus untuk mengarahkan mereka seturut dengan tujuan yang ditetapkan oleh korporasi. Jarak individu-organisasi ini dilihat sebagai bagian dari praktik hegemoni. Burrell dan Morgan (1979) mengidentifikasi bahwa sistem organisasi kapitalistik cenderung menciptakan struktur sosial yang membatasi kebebasan individu dan mempromosikan kepentingan organisasi yang dianggap lebih realistis dan mulia dari sekadar nilai-nilai individu yang lebih mendalam, seperti otonomi, kreativitas, dan kebutuhan eksistensi.
Cara pikir dan kerja organisasi yang mekanis tersebut rentan menimbulkan alienasi pada level individu; seseorang menjadi terasing dari sistem nilai organisasional yang cenderung bersifat impersonal (Saks, 2019). Alienasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan psikologis individu terkait makna dan aktualisasi diri dengan rules organisasi yang menekankan pada efisiensi, kepatuhan, dan target pencapaian (Gabriel, 1999). Perlahan tapi pasti, kondisi keterasingan ini dapat mengarah pada kehampaan makna individu (karyawan) sebagai subjek.
***
Persyaratan kerja atau job requirement umumnya dianggap “filter” untuk mengundang keterlibatan individu sebagai anggota organisasi. Persyaratan ini menetapkan apa yang diharapkan organisasi dari individu dalam menjalankan fungsinya. Menurut Warr (2007), persyaratan kerja sering kali diformulasikan berdasarkan kebutuhan organisasi yang bersifat fungsional dan objektif. Dalam banyak kasus, persyaratan kerja lebih difokuskan pada efisiensi aktivitas peran dan kerja. Bisa dimaknai bahwa job requirement memiliki kecenderungan organisasi untuk menginstrumentalisasi manusia sebagai sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi (Alvesson & Willmott, 1992).
Pendekatan terhadap organisasi yang mengutamakan efisiensi seringkali membatasi ruang bagi individu untuk mengekspresikan otonomi, kreativitas, dan kebutuhan personal mereka dalam lingkungan kerja. Sebagai contoh, Edwards (1979) mencatat bahwa struktur pekerjaan yang kaku dan berorientasi pada kontrol menciptakan suatu lingkungan di mana pekerja dipandang lebih sebagai bagian dari “mesin” organisasi, yang dapat dengan mudah dipindah atau digantikan apabila mengalami deklinasi dengan standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Marcuse (1964), yang menyoroti bahwa organisasi modern cenderung menyederhanakan manusia menjadi sekadar alat produksi serta mengabaikan emosi mereka.
Kritik terhadap praktik mekanis organisasi terarah pada abainya sistem organisasi dalam mempertimbangkan aspek subjektif individu. Pengabaian tersebut berpotensi menciptakan “dehumanisasi” di tempat kerja, di mana karyawan merasa kehilangan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka (Gabriel, 1999). Burrell dan Morgan (1979; Alvesson & Deetz, 2000) menegaskan bahwa praktik-praktik organisasi yang hanya berfokus pada dimensi fungsional mengabaikan potensi unik manusia menjadi alasan bagi terjadinya alienasi pekerja; pekerja menjadi merasa bukan dirinya di tempat kerja. Pada akhirnya, ruang bagi eksplorasi makna individu menemui jalan buntu.
Sementara itu, job qualification menjadi syarat kemampuan yang harus dipenuhi calon karyawan agar dapat diterima dalam suatu peran organisasi. Kualifikasi ini menentukan apakah seseorang layak untuk bertugas secara spesifik dalam tata peran organisasi. Sementara keinginan seseorang bergabung dalam organisasi karena berbagai tuntutan hidupnya, tetapi di sisi lain ia cenderung melakukan penyesuaian dengan melakukan banyak hal supaya selaras dengan kriteria kualifikasi tugas. Mempersiapkan wawancara kerja, melatih dan mengerjakan serangkaian tes seleksi, bahkan juga mengumpulkan info sebanyak mungkin tentang organisasi yang hendak dimasukinya untuk membangun skenario impresi positif: individu rela menjadi “yang bukan dirinya” (Ryan & Deci, 2000). Semua diyakini calon karyawan sebagai perjuangan mencari kerja.
Sah-sah saja bahwa dalam logika rekrutmen organisasi, kecocokan antara persyaratan kerja dan kualifikasi individu dianggap sebagai mekanisme handal dalam mengintegrasikan seseorang ke dalam organisasi sesuai dengan jargon “right man on right place”. Senyatanya penyesuaian ini mengabaikan dimensi personal dari individu, seperti aspirasi pribadi, tujuan hidup, dan makna eksistensial yang barangkali tiada pernah dipertimbangkan oleh organisasi.
Kristof-Brown dkk. (2005) menunjukkan jika kesesuaian antara nilai individu dan organisasi, atau yang dikenal sebagai “person-organization fit,” diyakini akan berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Ketika individu merasa bahwa nilai-nilai mereka sejalan dengan misi dan tujuan organisasi, mereka lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Sebaliknya, ketidakcocokan nilai ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, stres, dan bahkan pengunduran diri, sehingga menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan antara individu dan organisasi (Edwards & Cable, 2009).
Pada sisi lain, kesesuaian mekanis ini sering kali mengabaikan realitas sosial dan kekuasaan yang ada dalam organisasi. Alvesson dan Willmott (1992) berpendapat bahwa kesesuaian dalam konteks mekanis lebih mungkin adalah proses pencocokan, bukan sebuah kecocokan. Hal ini bisa tampak dari kecenderungan individu yang terpaksa menyesuaikan diri dengan norma dan nilai organisasi karena tuntutan normatif yang lebih besar untuk dapat bekerja, produktif, atau hidup mandiri yang telah dikonstruksi oleh alam pikiran sosial masyarakat yang berpihak pada logika praktis dan materialis (Pelser dkk., 2022).
Seleksi bersandar pada kualifikasi dan persyaratan tugas sebagai piranti organisasi merefleksikan bentuk dominasi simbolik, di mana organisasi memiliki akses lebih besar untuk menentukan persyaratan yang diperlukan, sementara calon pekerja menjadi pihak yang berada dalam posisi “harus menyesuaikan” (Campbell, 2009). Dalam konteks ini, gesekan yang disebut sebagai “value incongruence” muncul ketika nilai-nilai individu dan organisasi tidak selaras, yang dapat memengaruhi komitmen dan keterlibatan individu dalam organisasi (Van Vianen, 2018). Pada sisi lain menjalani kualifikasi tugas yang barangkali adalah bukan diri, sangat mungkin pada saatnya individu mengalami persoalan menyesuaikan diri dengan standar organisasi (Gagné & Deci, 2005). Dari ketegangan dan rasa bosan bisa berkembang menjadi “kekosongan eksistensial” di mana individu merasa bahwa apa yang selama ini dilakukan tidak berkontribusi pada kekhasan pribadi karena perbedaan dinamika diri dan organisasi (Gabriel, 1999).
***
Nilai dan tujuan individu lebih terkait erat dengan makna kehidupan. Bagi individu, bekerja tidak hanya soal produktivitas atau mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga soal menemukan makna yang mendalam dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, individu mencari cara untuk mengekspresikan diri, memenuhi aspirasi, dan mengejar tujuan yang selaras dengan nilai-nilai inti mereka. Frankl (1963) menyatakan bahwa pencarian makna adalah motivasi dasar bagi manusia. Frankl berargumen bahwa ketika individu menemukan makna dalam hidupnya, mereka akan lebih mampu mengatasi tantangan dalam lingkungan sosialnya. Dalam rangka menemukan makna, salah satu yang ditawarkan oleh Frankl (1980/2019) adalah lewat kerja yang kreatif dan produktif.
Di sisi lain, organisasi cenderung berfokus pada tujuan fungsional yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Dalam upaya untuk mencapai hasil yang optimal, organisasi sering kali merumuskan visi dan misi yang bersifat strategis dan terkadang mengabaikan nilai-nilai pribadi karyawannya. Meyer dan Allen (1991) mengungkapkan bahwa alasan kuat dari karakter impersonal nilai organisasi adalah karena sikap profesionalitas dan cara kerja yang rasional objektif. Profesional dijelaskan dengan alasan bisnis (bukan personal); dan rasional objektif lebih sebagai cara kerja yang teratur, terukur dan tangible.
***
Upaya mengatasi potensi ketidakselarasan antara nilai individu dan organisasi diberi istilah “komitmen” yang sering kali digunakan sebagai jembatan untuk memadukannya. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan psikologis yang mengikat individu pada organisasi dan mengarahkan tindakan mereka agar sesuai dengan tujuan organisasi (Meyer & Herscovitch, 2001). Dalam banyak kasus, komitmen ini dianggap sebagai sarana untuk mencapai sinergi antara individu dan organisasi. Dalam kenyataan praktisnya adalah penting untuk mempertimbangkan apakah komitmen ini benar-benar dihasilkan dari kesepakatan bersama antara organisasi dan individu, atau apakah lebih merupakan produk dari tuntutan organisasi yang diinstitusikan dalam kontrak kerja formal. Komitmen organisasi adalah konsep yang mendorong kepatuhan individu pada segenap rules dan cara kerja organisasi (Al-Jabari & Ghazzawi, 2019).
Komitmen lebih sering muncul sebagai tuntutan sepihak dari organisasi. Organisasi cenderung menggunakan kontrak kerja sebagai instrumen untuk menetapkan komitmen formal dari individu. Kontrak ini sering kali mencakup ekspektasi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Dilengkapi dengan strategi reward and punishment yang diterapkan untuk memastikan bahwa individu tetap terlibat dalam proses operasional organisasi (Amstrong, 2005; Deci & Ryan, 2000). Misalnya, sistem insentif yang berfokus pada pencapaian hasil yang terukur dapat menciptakan tekanan tambahan pada individu untuk beradaptasi dengan tujuan organisasi.
Deci dan Ryan (2000) menegaskan bahwa penggunaan strategi ini dapat menyebabkan individu merasa termotivasi secara ekstrinsik, tetapi bukan karena mereka terlibat secara emosional atau menemukan makna dalam pekerjaan mereka. Lebih jauh lagi, ketika komitmen dihasilkan melalui kontrak kerja dan strategi motivasi yang bersifat eksploitatif, individu mungkin mengalami “burnout” atau kelelahan emosional, yang berpotensi mendatangkan problem kesehatan mental (Maslach & Leiter, 2016)
Regulasi komitmen kerja umumnya berada di bawah lingkup tanggung jawab dan tugas PIO. Divisi seperti HRD (Human Resource Development), HRM (Human Resource Management), atau dalam bahasa konvensionalnya “bagian personalia” menjadi garda utama untuk merancang dan mengimplementasikan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen kerja karyawan. Cara kerja penegakan komitmen kerja umumnya mengutamakan aspek kuantitatif sebagai ukuran tinggi rendahnya komitmen. Bakker dan Demerouti (2017) menunjukkan bahwa strategi yang lebih umum diterapkan sering kali mengutamakan indeks produktivitas dan efisiensi sebagai indikator keberhasilan komitmen, sementara aspek-aspek kualitatif seperti kesejahteraan psikologis, makna kerja, dan hubungan sosial di tempat kerja dipandang sebagai hal yang sekunder. Sebagai konsekuensinya cara kerja kuantitatif (yang dianggap cepat, objektif, dan mudah dikomunikasikan) terbukti menciptakan lingkungan kerja yang terfokus pada pencapaian target, seiring dengan tekanan berlebih pada individu untuk memenuhi ekspektasi organisasi.
***
Perubahan zaman menciptakan banyak perubahan melalui dinamika perkembangan dan relasi antara organisasi dengan individu. Kehidupan organisasi dan individu bergerak secara dinamis, menciptakan perubahan baik dalam skala mikro maupun makro. Di tingkat mikro, individu di dalam organisasi sering kali mengalami dilema antara keinginan untuk mencapai tujuan pribadi dan tuntutan dari organisasi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Di tingkat makro, tren sosial dan budaya yang lebih luas dapat memengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan mereka. Ini menciptakan tantangan yang kompleks bagi para praktisi PIO, yang perlu menemukan cara untuk mengharmonisasikan nilai-nilai personal individu dengan nilai-nilai operasional organisasi.
Dalam upaya untuk mencapai harmoni ini, praktisi PIO perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada individu. Ini berarti tidak hanya mengandalkan strategi yang berfokus pada efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan psikologis dan aspirasi individu. Sebagaimana dinyatakan oleh Bénabou dan Tirole (2016), penting bagi organisasi untuk memahami bahwa motivasi individu tidak hanya dipengaruhi oleh insentif eksternal, tetapi juga oleh identitas dan nilai-nilai yang mereka anut. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman tentang kebutuhan psikologis dasar individu—seperti otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial—ke dalam struktur organisasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi ketidakselarasan antara individu dan organisasi.
Dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis, aransemen komitmen yang mampu mengakomodasi baik kepentingan individu maupun organisasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Komitmen bukan hanya sekadar kewajiban formal yang diatur dalam kontrak kerja, tetapi juga sebuah ikatan psikologis yang menciptakan rasa saling memiliki dan tujuan bersama antara individu dan organisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Van Vianen (2018) bahwa model komitmen yang efektif harus mampu memberikan keuntungan lewat menyelaraskan kepentingan individu dengan visi organisasi. Oleh karena itu, pengembangan aransemen komitmen yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.
Pendekatan apresiatif dalam mengelola hubungan antara individu dan organisasi memainkan peran kunci dalam menciptakan aransemen komitmen yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, apresiasi bukan hanya terbatas pada pengakuan atas kinerja individu, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap nilai dan aspirasi pribadi yang mereka bawa ke dalam organisasi. Menurut Wrzesniewski dan Dutton (2001), komitmen dan keterlibatan individu terhadap organisasi dapat ditingkatkan lewat pemberian makna pada pekerjaan. Dengan demikian, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya menilai kontribusi individu dari sudut pandang kinerja semata, tetapi juga memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan nilai-nilai dan tujuan pribadi mereka.
Salah satu tantangan utama bagi praktisi PIO adalah menciptakan model komitmen yang tidak hanya memprioritaskan produktivitas, tetapi juga menghargai martabat dan kebutuhan emosional individu di dalam organisasi. Sebagai contoh, peneliti seperti Bakker dan Demerouti (2017) menyarankan bahwa strategi pengelolaan komitmen harus melibatkan dukungan terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. Ini termasuk menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, mengembangkan keterampilan, dan merasakan hubungan sosial yang positif di tempat kerja. Ketika individu merasa dihargai dan diakui sebagai bagian integral dari organisasi, mereka cenderung lebih berkomitmen dan terlibat secara emosional dalam tugas mereka.
Pentingnya model komitmen yang berkelanjutan juga ditekankan oleh Kahn (1990), yang menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam organisasi berkaitan erat dengan bagaimana mereka memaknai peran mereka. Bagi Kahn, keterlibatan hanya mungkin terjadi saat individu merasa terhubung secara emosional, kognitif, dan fisik dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, menciptakan aransemen komitmen yang menghargai pengalaman subjektif individu adalah langkah krusial dalam mengurangi ketidakselarasan antara tujuan organisasi dan aspirasi individu (Newton dkk., 2022).
Membangun aransemen komitmen yang berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi individu dan organisasi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan kerja secara keseluruhan. Ketika individu merasa terlibat dan terhubung dengan organisasi, mereka akan lebih mungkin untuk berinvestasi dalam kemajuan dan inovasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam konteks ini, komitmen menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan individu dan organisasi, memungkinkan keduanya untuk tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang saling mendukung (Afshari dkk., 2019).
***
Bukan sebuah kebetulan bahwa editorial dalam edisi kali ini membahas soal PIO. Empat dari tujuh laporan penelitian dalam jurnal ini biasanya dikategorikan dalam bidang PIO. Melalui analisis kuantitatif, keempat jurnal tersebut memeriksa bagaimana variabel-variabel diletakkan secara terisolasi dari konteks sosiohistoris yang dialami subjek. Problem yang masih bisa dielaborasi adalah terkait dengan pemahaman bahwa fenomena dalam psikologi kerja sukar untuk diisolasi ke dalam variabel-variabel yang justru membuat abstrak pengalaman material para pekerja. Bahkan, pendekatan kontemporer lewat psikologi kognitif dan neurosains dalam pengalaman sehari-hari sering kali luput dalam memotret aturan sosial yang mengaktivasi pengalaman emosional dan makna yang terkandung dalam pengalaman tersebut bagi subjek. Oleh karena itu, alangkah bijaknya para pembaca yang budiman membaca sembari mencermati apa yang belum terpotret dari pemngalaman yang di-variabel-kan tersebut.
Pada artikel pertama, Yunita Rahmadina dan Fathul Himam meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai, khususnya kualitas dan kuantitas kerja, berdasarkan model prediktor kinerja Blumberg dan Pringle (1982). Data dari 147 pegawai dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM), menunjukkan bahwa kemauan (work engagement dan job involvement), kesempatan (kepemimpinan transformasional dan transaksional), dan kapasitas (kecerdasan emosional) signifikan dalam memprediksi kinerja pegawai.
Artikel kedua berjudul “Ethnocentrism Bias on Consumer Perception of Service Quality and Intention to Buy” ditulis oleh Fernanda Putri Gisela dan Rahmat Hidayat. Studi ini mengeksplorasi bagaimana bias etnosentrisme memengaruhi persepsi kualitas layanan dan intensi membeli. Meskipun tidak ditemukan perbedaan signifikan antara kelompok budaya Sunda dan Surabaya terhadap persepsi layanan dan intensi beli, ditemukan bahwa konsumen lebih menyukai frontliner dari budaya yang sama.
Jeremia Simatupang dan Pratista Arya Satwika menulis artikel ketiga yang mengeksplorasi pengaruh kepemimpinan transformasional dan kualitas kehidupan kerja terhadap keterlibatan pegawai generasi Z. Analisis regresi menunjukkan hubungan yang signifikan antara kedua faktor tersebut dan keterlibatan pegawai, menekankan pentingnya strategi untuk meningkatkan keterlibatan pegawai generasi Z.
Pada artikel berjudul “Gambaran Penerapan Pola Asuh Orang Tua dengan Anak Attention Deficit/Hyperactivity Disorder”, yakni artikel keempat, Diandra Paralea dan Penny Handayani mengkaji pola asuh orang tua terhadap anak dengan ADHD. Temuan menunjukkan bahwa orang tua menerapkan pendekatan asuh yang bervariasi berdasarkan situasi. Ibu lebih terlibat dalam kegiatan harian anak, sementara ayah cenderung fokus pada aspek disiplin.
Artikel kelima ditulis oleh Rizky Anggia Murni Tri Astuti. Kedua penulis meneliti hubungan antara komitmen afektif dan perilaku kewargaan organisasi (organizational citizenship behavior; OCB) di kalangan karyawan. Analisis menunjukkan bahwa komitmen afektif memiliki pengaruh signifikan terhadap OCB, menunjukkan pentingnya komitmen afektif dalam meningkatkan perilaku ekstra peran di tempat kerja.
Artikel keenam berjudul “Otak Bilingual: Sinergi Dwibahasa dalam Meningkatkan Fungsi Eksekutif”. Artikel yang ditulis oleh Elisabeth Dwi Anggraeni dan Selvi Sumardin ini meninjau bagaimana kemampuan bilingual meningkatkan fungsi eksekutif, terutama dalam kontrol inhibisi, memori kerja, dan fleksibilitas kognitif. Bilingualisme ditemukan memiliki dampak positif pada perkembangan kognitif, seperti peningkatan kemampuan berpikir kritis dan fleksibilitas mental.
Dalam artikel terakhir, atau ketujuh, Antonius Nandiwardana melakukan analisis bibliometrik pada penelitian mindfulness dalam neuropsikologi. Dari 929 dokumen yang dianalisis, ditemukan tren penelitian mindfulness yang semakin meningkat dengan fokus pada depresi, meditasi, dan fungsi eksekutif. Temuan ini memberi wawasan tentang tren serta kolaborasi dalam penelitian mindfulness.
***
Problem yang sering kali muncul dalam PIO adalah absennya kajian mengenai kerja yang bersifat historis dan kultural. Fokus pada produktivitas karyawan menjadi norma utama yang diagung-agungkan oleh para praktisi dan peneliti PIO. Sementara itu, sejarah konsep “kerja” yang berubah dari masa ke masa dan membentuk mentalitas manusia merupakan kajian yang sering kali luput untuk dibicarakan. Sebagai contoh, dalam bukunya, Komlosy (2018) menunjukkan bahwa pada abad ke-15, etika kerja Kristen mulai menguat. Muncul gagasan ora et labora yang menegaskan bahwa kerja yang tidak dibayar memiliki konotasi sebagai kerja yang suci. Gagasan lain yang muncul adalah bahwa malas adalah dosa. Perubahan konsep kemudian terjadi pada masa Revolusi Saintifik abad ke-15 dan ke-16 yang memahami kerja, buruh, dan teknologi sebagai kondisi di mana manusia bisa menaklukkan alam. Nilai baru yang menguat dalam rangka mencapai kebahagiaan adalah rajin, komitmen, dan ketekunan (industriousness). Kerja kemudian dianggap sebagai sesuatu yang utilitarian dan bentuk implementasi ekonomi nasional (merkantilisme). Kerja merupakan cara orang menjadi bahagia dan bebas. Kerja diukur dari pendapatan ekonomi dan harus produktif. Karenanya, kerja bertujuan menciptakan dan mengakumulasikan kapital. Dalam rangka reproduksi nilai-nilai kapitalistik kemudian kerja dipisahkan dari tanggung-jawab sosial.
Guna mencermati kembali bagaimana kerja-kerja industri dan organisasi kontemporer, orang yang berkecimpung dalam PIO perlu untuk melihat kembali mode produksi dan sistem yang beroperasi dalam dunia kerja saat ini. Tokoh psikologi seperti Erich Fromm (1900-1980) bisa menjadi acuan untuk memahami bagaimana sistem kerja berbasis kapitalisme yang hari ini mendominasi dan menghegemoni sebagian besar kerja-kerja industri dan mengubah lanskap mental manusia (Fromm, 1961/2004). Sebagai sebuah sistem yang besar, kapitalisme juga melahirkan ideologi-ideologi baru yang patut menjadi perhatian para peneliti, misalnya neoliberalisme (Ratner, 2019). Dalam kondisi neoliberalisme, muncul gagasan work-life balance yang memisahkan antara “kerja” (work) dan “kehidupan” (life) (Patria, 2024). Dengan kata lain kerja dan kehidupan bukan sesuatu yang selaras, melainkan sesuatu yang bersifat dikotomis. Oleh karenanya, bekerja untuk menemukan makna sebagaimana digagas Frankl (1980/2019) justru dijauhkan dari lewat semangat neoliberalisme.
Bukan sebagaimana gagasan Komlosy (2018), studi PIO yang dominan dalam Psikologi Karir. Psikologi Karir berbeda dengan Psikologi Kerja (Work Psychology). Selama ini dalam penelitian soal lingkungan kerja dan pekerjaan, psikologi lebih didominasi oleh Psikologi Karir. Apa yang dikerjakan dalam Psikologi Karir adalah membuat pekerja menjadi lebih produktif, demi kepentingan institusi. Sementara itu, Psikologi Kerja berfokus pada bekerja sebagai aktivitas sentral manusia secara sosio-kultural dan melekat erat dalam domain kehidupan. Semua aspek kerja, termasuk kerja dibayar dan tidak dibayar, dipelajari dalam Psikologi Kerja. Secara khusus, Psikologi Kerja fokus pada opresi dan hambatan sosial dalam bekerja alih-alih pada produktivitas (Prilleltensky & Stead, 2013).
***
Pikiran soal membangun komitmen yang mengusung harmoni antara organisasi dan individu adalah idealisme. Tentu saja ide tulisan di atas tampak sebagai sebuah utopia dalam praktis organisasi modern yang cenderung mengutamakan produktivitas objektif. Sementara gerak dinamika subjek (karyawan) adalah padat keragaman dan sulit dipastikan. Akan tetapi, ide soal harmoni ini bisa menjadi konsiderasi bagi para praktisi pengembangan organisasi yang peduli pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis individu sebagai anggota organisasi. Idealisme ini barangkali bisa memberikan inspirasi untuk selalu menegakkan tujuan psikologi sebagai ilmu yang berpihak pada manusia. Ngono yo ngono ning ojo ngono.
Namun, apakah mungkin tujuan organisasi benar-benar dapat mewakili tujuan individu? Pertanyaan ini layak dikaji dalam praktik organisasi hari ini, di mana keduanya menjadi entitas yang sering kali berada dalam kondisi berhadapan: subjek individu dan organisasi. Dalam banyak kajian, relasi antara individu dan organisasi lebih sering terjadi pelemahan otonomi individu demi kepentingan organisasi yang semakin kuat (Kahn, 1990). Logika organisasi cenderung meletakkan posisi individu di bawah kepentingan yang dikendalikan oleh owner, atau sesuai dengan “kehendak” organisasinya (Deci et al., 2017).
Secara operasional, kepentingan owner, pemilik modal, atau pemberi kerja (employer) ini diterjemahkan ke dalam visi dan misi organisasi, untuk kemudian dipromosikan sebagai rules yang meregulasi individu di dalamya (Akter, 2021). Kepentingan yang mewujud dalam ide-ide besar tentang kemajuan, inovasi, dan efisiensi versi organisasi terkesan jarang mempertimbangkan aspirasi dan makna personal individu dalam posisinya sebagai anggota organisasi (baca: pekerja, buruh, karyawan, atau employee). Dari sudut pandang kritis, perspektif ini mengarah pada suatu bentuk kontrol hegemonik di mana individu dikondisikan untuk menerima dan melaksanakan aturan dan nilai-nilai organisasi tanpa perlu mempertanyakan. Sebagaimana dicatat oleh Lewandowski (2017), organisasi sering menggunakan mekanisme ideologis untuk membentuk nilai identitas individu sebagai karyawan, sebagai bahasa halus untuk mengarahkan mereka seturut dengan tujuan yang ditetapkan oleh korporasi. Jarak individu-organisasi ini dilihat sebagai bagian dari praktik hegemoni. Burrell dan Morgan (1979) mengidentifikasi bahwa sistem organisasi kapitalistik cenderung menciptakan struktur sosial yang membatasi kebebasan individu dan mempromosikan kepentingan organisasi yang dianggap lebih realistis dan mulia dari sekadar nilai-nilai individu yang lebih mendalam, seperti otonomi, kreativitas, dan kebutuhan eksistensi.
Cara pikir dan kerja organisasi yang mekanis tersebut rentan menimbulkan alienasi pada level individu; seseorang menjadi terasing dari sistem nilai organisasional yang cenderung bersifat impersonal (Saks, 2019). Alienasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan psikologis individu terkait makna dan aktualisasi diri dengan rules organisasi yang menekankan pada efisiensi, kepatuhan, dan target pencapaian (Gabriel, 1999). Perlahan tapi pasti, kondisi keterasingan ini dapat mengarah pada kehampaan makna individu (karyawan) sebagai subjek.
***
Persyaratan kerja atau job requirement umumnya dianggap “filter” untuk mengundang keterlibatan individu sebagai anggota organisasi. Persyaratan ini menetapkan apa yang diharapkan organisasi dari individu dalam menjalankan fungsinya. Menurut Warr (2007), persyaratan kerja sering kali diformulasikan berdasarkan kebutuhan organisasi yang bersifat fungsional dan objektif. Dalam banyak kasus, persyaratan kerja lebih difokuskan pada efisiensi aktivitas peran dan kerja. Bisa dimaknai bahwa job requirement memiliki kecenderungan organisasi untuk menginstrumentalisasi manusia sebagai sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi (Alvesson & Willmott, 1992).
Pendekatan terhadap organisasi yang mengutamakan efisiensi seringkali membatasi ruang bagi individu untuk mengekspresikan otonomi, kreativitas, dan kebutuhan personal mereka dalam lingkungan kerja. Sebagai contoh, Edwards (1979) mencatat bahwa struktur pekerjaan yang kaku dan berorientasi pada kontrol menciptakan suatu lingkungan di mana pekerja dipandang lebih sebagai bagian dari “mesin” organisasi, yang dapat dengan mudah dipindah atau digantikan apabila mengalami deklinasi dengan standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Marcuse (1964), yang menyoroti bahwa organisasi modern cenderung menyederhanakan manusia menjadi sekadar alat produksi serta mengabaikan emosi mereka.
Kritik terhadap praktik mekanis organisasi terarah pada abainya sistem organisasi dalam mempertimbangkan aspek subjektif individu. Pengabaian tersebut berpotensi menciptakan “dehumanisasi” di tempat kerja, di mana karyawan merasa kehilangan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka (Gabriel, 1999). Burrell dan Morgan (1979; Alvesson & Deetz, 2000) menegaskan bahwa praktik-praktik organisasi yang hanya berfokus pada dimensi fungsional mengabaikan potensi unik manusia menjadi alasan bagi terjadinya alienasi pekerja; pekerja menjadi merasa bukan dirinya di tempat kerja. Pada akhirnya, ruang bagi eksplorasi makna individu menemui jalan buntu.
Sementara itu, job qualification menjadi syarat kemampuan yang harus dipenuhi calon karyawan agar dapat diterima dalam suatu peran organisasi. Kualifikasi ini menentukan apakah seseorang layak untuk bertugas secara spesifik dalam tata peran organisasi. Sementara keinginan seseorang bergabung dalam organisasi karena berbagai tuntutan hidupnya, tetapi di sisi lain ia cenderung melakukan penyesuaian dengan melakukan banyak hal supaya selaras dengan kriteria kualifikasi tugas. Mempersiapkan wawancara kerja, melatih dan mengerjakan serangkaian tes seleksi, bahkan juga mengumpulkan info sebanyak mungkin tentang organisasi yang hendak dimasukinya untuk membangun skenario impresi positif: individu rela menjadi “yang bukan dirinya” (Ryan & Deci, 2000). Semua diyakini calon karyawan sebagai perjuangan mencari kerja.
Sah-sah saja bahwa dalam logika rekrutmen organisasi, kecocokan antara persyaratan kerja dan kualifikasi individu dianggap sebagai mekanisme handal dalam mengintegrasikan seseorang ke dalam organisasi sesuai dengan jargon “right man on right place”. Senyatanya penyesuaian ini mengabaikan dimensi personal dari individu, seperti aspirasi pribadi, tujuan hidup, dan makna eksistensial yang barangkali tiada pernah dipertimbangkan oleh organisasi.
Kristof-Brown dkk. (2005) menunjukkan jika kesesuaian antara nilai individu dan organisasi, atau yang dikenal sebagai “person-organization fit,” diyakini akan berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Ketika individu merasa bahwa nilai-nilai mereka sejalan dengan misi dan tujuan organisasi, mereka lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Sebaliknya, ketidakcocokan nilai ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, stres, dan bahkan pengunduran diri, sehingga menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan antara individu dan organisasi (Edwards & Cable, 2009).
Pada sisi lain, kesesuaian mekanis ini sering kali mengabaikan realitas sosial dan kekuasaan yang ada dalam organisasi. Alvesson dan Willmott (1992) berpendapat bahwa kesesuaian dalam konteks mekanis lebih mungkin adalah proses pencocokan, bukan sebuah kecocokan. Hal ini bisa tampak dari kecenderungan individu yang terpaksa menyesuaikan diri dengan norma dan nilai organisasi karena tuntutan normatif yang lebih besar untuk dapat bekerja, produktif, atau hidup mandiri yang telah dikonstruksi oleh alam pikiran sosial masyarakat yang berpihak pada logika praktis dan materialis (Pelser dkk., 2022).
Seleksi bersandar pada kualifikasi dan persyaratan tugas sebagai piranti organisasi merefleksikan bentuk dominasi simbolik, di mana organisasi memiliki akses lebih besar untuk menentukan persyaratan yang diperlukan, sementara calon pekerja menjadi pihak yang berada dalam posisi “harus menyesuaikan” (Campbell, 2009). Dalam konteks ini, gesekan yang disebut sebagai “value incongruence” muncul ketika nilai-nilai individu dan organisasi tidak selaras, yang dapat memengaruhi komitmen dan keterlibatan individu dalam organisasi (Van Vianen, 2018). Pada sisi lain menjalani kualifikasi tugas yang barangkali adalah bukan diri, sangat mungkin pada saatnya individu mengalami persoalan menyesuaikan diri dengan standar organisasi (Gagné & Deci, 2005). Dari ketegangan dan rasa bosan bisa berkembang menjadi “kekosongan eksistensial” di mana individu merasa bahwa apa yang selama ini dilakukan tidak berkontribusi pada kekhasan pribadi karena perbedaan dinamika diri dan organisasi (Gabriel, 1999).
***
Nilai dan tujuan individu lebih terkait erat dengan makna kehidupan. Bagi individu, bekerja tidak hanya soal produktivitas atau mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga soal menemukan makna yang mendalam dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, individu mencari cara untuk mengekspresikan diri, memenuhi aspirasi, dan mengejar tujuan yang selaras dengan nilai-nilai inti mereka. Frankl (1963) menyatakan bahwa pencarian makna adalah motivasi dasar bagi manusia. Frankl berargumen bahwa ketika individu menemukan makna dalam hidupnya, mereka akan lebih mampu mengatasi tantangan dalam lingkungan sosialnya. Dalam rangka menemukan makna, salah satu yang ditawarkan oleh Frankl (1980/2019) adalah lewat kerja yang kreatif dan produktif.
Di sisi lain, organisasi cenderung berfokus pada tujuan fungsional yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Dalam upaya untuk mencapai hasil yang optimal, organisasi sering kali merumuskan visi dan misi yang bersifat strategis dan terkadang mengabaikan nilai-nilai pribadi karyawannya. Meyer dan Allen (1991) mengungkapkan bahwa alasan kuat dari karakter impersonal nilai organisasi adalah karena sikap profesionalitas dan cara kerja yang rasional objektif. Profesional dijelaskan dengan alasan bisnis (bukan personal); dan rasional objektif lebih sebagai cara kerja yang teratur, terukur dan tangible.
***
Upaya mengatasi potensi ketidakselarasan antara nilai individu dan organisasi diberi istilah “komitmen” yang sering kali digunakan sebagai jembatan untuk memadukannya. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan psikologis yang mengikat individu pada organisasi dan mengarahkan tindakan mereka agar sesuai dengan tujuan organisasi (Meyer & Herscovitch, 2001). Dalam banyak kasus, komitmen ini dianggap sebagai sarana untuk mencapai sinergi antara individu dan organisasi. Dalam kenyataan praktisnya adalah penting untuk mempertimbangkan apakah komitmen ini benar-benar dihasilkan dari kesepakatan bersama antara organisasi dan individu, atau apakah lebih merupakan produk dari tuntutan organisasi yang diinstitusikan dalam kontrak kerja formal. Komitmen organisasi adalah konsep yang mendorong kepatuhan individu pada segenap rules dan cara kerja organisasi (Al-Jabari & Ghazzawi, 2019).
Komitmen lebih sering muncul sebagai tuntutan sepihak dari organisasi. Organisasi cenderung menggunakan kontrak kerja sebagai instrumen untuk menetapkan komitmen formal dari individu. Kontrak ini sering kali mencakup ekspektasi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Dilengkapi dengan strategi reward and punishment yang diterapkan untuk memastikan bahwa individu tetap terlibat dalam proses operasional organisasi (Amstrong, 2005; Deci & Ryan, 2000). Misalnya, sistem insentif yang berfokus pada pencapaian hasil yang terukur dapat menciptakan tekanan tambahan pada individu untuk beradaptasi dengan tujuan organisasi.
Deci dan Ryan (2000) menegaskan bahwa penggunaan strategi ini dapat menyebabkan individu merasa termotivasi secara ekstrinsik, tetapi bukan karena mereka terlibat secara emosional atau menemukan makna dalam pekerjaan mereka. Lebih jauh lagi, ketika komitmen dihasilkan melalui kontrak kerja dan strategi motivasi yang bersifat eksploitatif, individu mungkin mengalami “burnout” atau kelelahan emosional, yang berpotensi mendatangkan problem kesehatan mental (Maslach & Leiter, 2016)
Regulasi komitmen kerja umumnya berada di bawah lingkup tanggung jawab dan tugas PIO. Divisi seperti HRD (Human Resource Development), HRM (Human Resource Management), atau dalam bahasa konvensionalnya “bagian personalia” menjadi garda utama untuk merancang dan mengimplementasikan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen kerja karyawan. Cara kerja penegakan komitmen kerja umumnya mengutamakan aspek kuantitatif sebagai ukuran tinggi rendahnya komitmen. Bakker dan Demerouti (2017) menunjukkan bahwa strategi yang lebih umum diterapkan sering kali mengutamakan indeks produktivitas dan efisiensi sebagai indikator keberhasilan komitmen, sementara aspek-aspek kualitatif seperti kesejahteraan psikologis, makna kerja, dan hubungan sosial di tempat kerja dipandang sebagai hal yang sekunder. Sebagai konsekuensinya cara kerja kuantitatif (yang dianggap cepat, objektif, dan mudah dikomunikasikan) terbukti menciptakan lingkungan kerja yang terfokus pada pencapaian target, seiring dengan tekanan berlebih pada individu untuk memenuhi ekspektasi organisasi.
***
Perubahan zaman menciptakan banyak perubahan melalui dinamika perkembangan dan relasi antara organisasi dengan individu. Kehidupan organisasi dan individu bergerak secara dinamis, menciptakan perubahan baik dalam skala mikro maupun makro. Di tingkat mikro, individu di dalam organisasi sering kali mengalami dilema antara keinginan untuk mencapai tujuan pribadi dan tuntutan dari organisasi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Di tingkat makro, tren sosial dan budaya yang lebih luas dapat memengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan mereka. Ini menciptakan tantangan yang kompleks bagi para praktisi PIO, yang perlu menemukan cara untuk mengharmonisasikan nilai-nilai personal individu dengan nilai-nilai operasional organisasi.
Dalam upaya untuk mencapai harmoni ini, praktisi PIO perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada individu. Ini berarti tidak hanya mengandalkan strategi yang berfokus pada efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan psikologis dan aspirasi individu. Sebagaimana dinyatakan oleh Bénabou dan Tirole (2016), penting bagi organisasi untuk memahami bahwa motivasi individu tidak hanya dipengaruhi oleh insentif eksternal, tetapi juga oleh identitas dan nilai-nilai yang mereka anut. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman tentang kebutuhan psikologis dasar individu—seperti otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial—ke dalam struktur organisasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi ketidakselarasan antara individu dan organisasi.
Dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis, aransemen komitmen yang mampu mengakomodasi baik kepentingan individu maupun organisasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Komitmen bukan hanya sekadar kewajiban formal yang diatur dalam kontrak kerja, tetapi juga sebuah ikatan psikologis yang menciptakan rasa saling memiliki dan tujuan bersama antara individu dan organisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Van Vianen (2018) bahwa model komitmen yang efektif harus mampu memberikan keuntungan lewat menyelaraskan kepentingan individu dengan visi organisasi. Oleh karena itu, pengembangan aransemen komitmen yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.
Pendekatan apresiatif dalam mengelola hubungan antara individu dan organisasi memainkan peran kunci dalam menciptakan aransemen komitmen yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, apresiasi bukan hanya terbatas pada pengakuan atas kinerja individu, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap nilai dan aspirasi pribadi yang mereka bawa ke dalam organisasi. Menurut Wrzesniewski dan Dutton (2001), komitmen dan keterlibatan individu terhadap organisasi dapat ditingkatkan lewat pemberian makna pada pekerjaan. Dengan demikian, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya menilai kontribusi individu dari sudut pandang kinerja semata, tetapi juga memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan nilai-nilai dan tujuan pribadi mereka.
Salah satu tantangan utama bagi praktisi PIO adalah menciptakan model komitmen yang tidak hanya memprioritaskan produktivitas, tetapi juga menghargai martabat dan kebutuhan emosional individu di dalam organisasi. Sebagai contoh, peneliti seperti Bakker dan Demerouti (2017) menyarankan bahwa strategi pengelolaan komitmen harus melibatkan dukungan terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. Ini termasuk menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, mengembangkan keterampilan, dan merasakan hubungan sosial yang positif di tempat kerja. Ketika individu merasa dihargai dan diakui sebagai bagian integral dari organisasi, mereka cenderung lebih berkomitmen dan terlibat secara emosional dalam tugas mereka.
Pentingnya model komitmen yang berkelanjutan juga ditekankan oleh Kahn (1990), yang menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam organisasi berkaitan erat dengan bagaimana mereka memaknai peran mereka. Bagi Kahn, keterlibatan hanya mungkin terjadi saat individu merasa terhubung secara emosional, kognitif, dan fisik dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, menciptakan aransemen komitmen yang menghargai pengalaman subjektif individu adalah langkah krusial dalam mengurangi ketidakselarasan antara tujuan organisasi dan aspirasi individu (Newton dkk., 2022).
Membangun aransemen komitmen yang berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi individu dan organisasi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan kerja secara keseluruhan. Ketika individu merasa terlibat dan terhubung dengan organisasi, mereka akan lebih mungkin untuk berinvestasi dalam kemajuan dan inovasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam konteks ini, komitmen menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan individu dan organisasi, memungkinkan keduanya untuk tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang saling mendukung (Afshari dkk., 2019).
***
Bukan sebuah kebetulan bahwa editorial dalam edisi kali ini membahas soal PIO. Empat dari tujuh laporan penelitian dalam jurnal ini biasanya dikategorikan dalam bidang PIO. Melalui analisis kuantitatif, keempat jurnal tersebut memeriksa bagaimana variabel-variabel diletakkan secara terisolasi dari konteks sosiohistoris yang dialami subjek. Problem yang masih bisa dielaborasi adalah terkait dengan pemahaman bahwa fenomena dalam psikologi kerja sukar untuk diisolasi ke dalam variabel-variabel yang justru membuat abstrak pengalaman material para pekerja. Bahkan, pendekatan kontemporer lewat psikologi kognitif dan neurosains dalam pengalaman sehari-hari sering kali luput dalam memotret aturan sosial yang mengaktivasi pengalaman emosional dan makna yang terkandung dalam pengalaman tersebut bagi subjek. Oleh karena itu, alangkah bijaknya para pembaca yang budiman membaca sembari mencermati apa yang belum terpotret dari pemngalaman yang di-variabel-kan tersebut.
Pada artikel pertama, Yunita Rahmadina dan Fathul Himam meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai, khususnya kualitas dan kuantitas kerja, berdasarkan model prediktor kinerja Blumberg dan Pringle (1982). Data dari 147 pegawai dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM), menunjukkan bahwa kemauan (work engagement dan job involvement), kesempatan (kepemimpinan transformasional dan transaksional), dan kapasitas (kecerdasan emosional) signifikan dalam memprediksi kinerja pegawai.
Artikel kedua berjudul “Ethnocentrism Bias on Consumer Perception of Service Quality and Intention to Buy” ditulis oleh Fernanda Putri Gisela dan Rahmat Hidayat. Studi ini mengeksplorasi bagaimana bias etnosentrisme memengaruhi persepsi kualitas layanan dan intensi membeli. Meskipun tidak ditemukan perbedaan signifikan antara kelompok budaya Sunda dan Surabaya terhadap persepsi layanan dan intensi beli, ditemukan bahwa konsumen lebih menyukai frontliner dari budaya yang sama.
Jeremia Simatupang dan Pratista Arya Satwika menulis artikel ketiga yang mengeksplorasi pengaruh kepemimpinan transformasional dan kualitas kehidupan kerja terhadap keterlibatan pegawai generasi Z. Analisis regresi menunjukkan hubungan yang signifikan antara kedua faktor tersebut dan keterlibatan pegawai, menekankan pentingnya strategi untuk meningkatkan keterlibatan pegawai generasi Z.
Pada artikel berjudul “Gambaran Penerapan Pola Asuh Orang Tua dengan Anak Attention Deficit/Hyperactivity Disorder”, yakni artikel keempat, Diandra Paralea dan Penny Handayani mengkaji pola asuh orang tua terhadap anak dengan ADHD. Temuan menunjukkan bahwa orang tua menerapkan pendekatan asuh yang bervariasi berdasarkan situasi. Ibu lebih terlibat dalam kegiatan harian anak, sementara ayah cenderung fokus pada aspek disiplin.
Artikel kelima ditulis oleh Rizky Anggia Murni Tri Astuti. Kedua penulis meneliti hubungan antara komitmen afektif dan perilaku kewargaan organisasi (organizational citizenship behavior; OCB) di kalangan karyawan. Analisis menunjukkan bahwa komitmen afektif memiliki pengaruh signifikan terhadap OCB, menunjukkan pentingnya komitmen afektif dalam meningkatkan perilaku ekstra peran di tempat kerja.
Artikel keenam berjudul “Otak Bilingual: Sinergi Dwibahasa dalam Meningkatkan Fungsi Eksekutif”. Artikel yang ditulis oleh Elisabeth Dwi Anggraeni dan Selvi Sumardin ini meninjau bagaimana kemampuan bilingual meningkatkan fungsi eksekutif, terutama dalam kontrol inhibisi, memori kerja, dan fleksibilitas kognitif. Bilingualisme ditemukan memiliki dampak positif pada perkembangan kognitif, seperti peningkatan kemampuan berpikir kritis dan fleksibilitas mental.
Dalam artikel terakhir, atau ketujuh, Antonius Nandiwardana melakukan analisis bibliometrik pada penelitian mindfulness dalam neuropsikologi. Dari 929 dokumen yang dianalisis, ditemukan tren penelitian mindfulness yang semakin meningkat dengan fokus pada depresi, meditasi, dan fungsi eksekutif. Temuan ini memberi wawasan tentang tren serta kolaborasi dalam penelitian mindfulness.
***
Problem yang sering kali muncul dalam PIO adalah absennya kajian mengenai kerja yang bersifat historis dan kultural. Fokus pada produktivitas karyawan menjadi norma utama yang diagung-agungkan oleh para praktisi dan peneliti PIO. Sementara itu, sejarah konsep “kerja” yang berubah dari masa ke masa dan membentuk mentalitas manusia merupakan kajian yang sering kali luput untuk dibicarakan. Sebagai contoh, dalam bukunya, Komlosy (2018) menunjukkan bahwa pada abad ke-15, etika kerja Kristen mulai menguat. Muncul gagasan ora et labora yang menegaskan bahwa kerja yang tidak dibayar memiliki konotasi sebagai kerja yang suci. Gagasan lain yang muncul adalah bahwa malas adalah dosa. Perubahan konsep kemudian terjadi pada masa Revolusi Saintifik abad ke-15 dan ke-16 yang memahami kerja, buruh, dan teknologi sebagai kondisi di mana manusia bisa menaklukkan alam. Nilai baru yang menguat dalam rangka mencapai kebahagiaan adalah rajin, komitmen, dan ketekunan (industriousness). Kerja kemudian dianggap sebagai sesuatu yang utilitarian dan bentuk implementasi ekonomi nasional (merkantilisme). Kerja merupakan cara orang menjadi bahagia dan bebas. Kerja diukur dari pendapatan ekonomi dan harus produktif. Karenanya, kerja bertujuan menciptakan dan mengakumulasikan kapital. Dalam rangka reproduksi nilai-nilai kapitalistik kemudian kerja dipisahkan dari tanggung-jawab sosial.
Guna mencermati kembali bagaimana kerja-kerja industri dan organisasi kontemporer, orang yang berkecimpung dalam PIO perlu untuk melihat kembali mode produksi dan sistem yang beroperasi dalam dunia kerja saat ini. Tokoh psikologi seperti Erich Fromm (1900-1980) bisa menjadi acuan untuk memahami bagaimana sistem kerja berbasis kapitalisme yang hari ini mendominasi dan menghegemoni sebagian besar kerja-kerja industri dan mengubah lanskap mental manusia (Fromm, 1961/2004). Sebagai sebuah sistem yang besar, kapitalisme juga melahirkan ideologi-ideologi baru yang patut menjadi perhatian para peneliti, misalnya neoliberalisme (Ratner, 2019). Dalam kondisi neoliberalisme, muncul gagasan work-life balance yang memisahkan antara “kerja” (work) dan “kehidupan” (life) (Patria, 2024). Dengan kata lain kerja dan kehidupan bukan sesuatu yang selaras, melainkan sesuatu yang bersifat dikotomis. Oleh karenanya, bekerja untuk menemukan makna sebagaimana digagas Frankl (1980/2019) justru dijauhkan dari lewat semangat neoliberalisme.
Bukan sebagaimana gagasan Komlosy (2018), studi PIO yang dominan dalam Psikologi Karir. Psikologi Karir berbeda dengan Psikologi Kerja (Work Psychology). Selama ini dalam penelitian soal lingkungan kerja dan pekerjaan, psikologi lebih didominasi oleh Psikologi Karir. Apa yang dikerjakan dalam Psikologi Karir adalah membuat pekerja menjadi lebih produktif, demi kepentingan institusi. Sementara itu, Psikologi Kerja berfokus pada bekerja sebagai aktivitas sentral manusia secara sosio-kultural dan melekat erat dalam domain kehidupan. Semua aspek kerja, termasuk kerja dibayar dan tidak dibayar, dipelajari dalam Psikologi Kerja. Secara khusus, Psikologi Kerja fokus pada opresi dan hambatan sosial dalam bekerja alih-alih pada produktivitas (Prilleltensky & Stead, 2013).
***
Pikiran soal membangun komitmen yang mengusung harmoni antara organisasi dan individu adalah idealisme. Tentu saja ide tulisan di atas tampak sebagai sebuah utopia dalam praktis organisasi modern yang cenderung mengutamakan produktivitas objektif. Sementara gerak dinamika subjek (karyawan) adalah padat keragaman dan sulit dipastikan. Akan tetapi, ide soal harmoni ini bisa menjadi konsiderasi bagi para praktisi pengembangan organisasi yang peduli pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis individu sebagai anggota organisasi. Idealisme ini barangkali bisa memberikan inspirasi untuk selalu menegakkan tujuan psikologi sebagai ilmu yang berpihak pada manusia. Ngono yo ngono ning ojo ngono.
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.24071/suksma.v5i3.10177
Refbacks
- There are currently no refbacks.